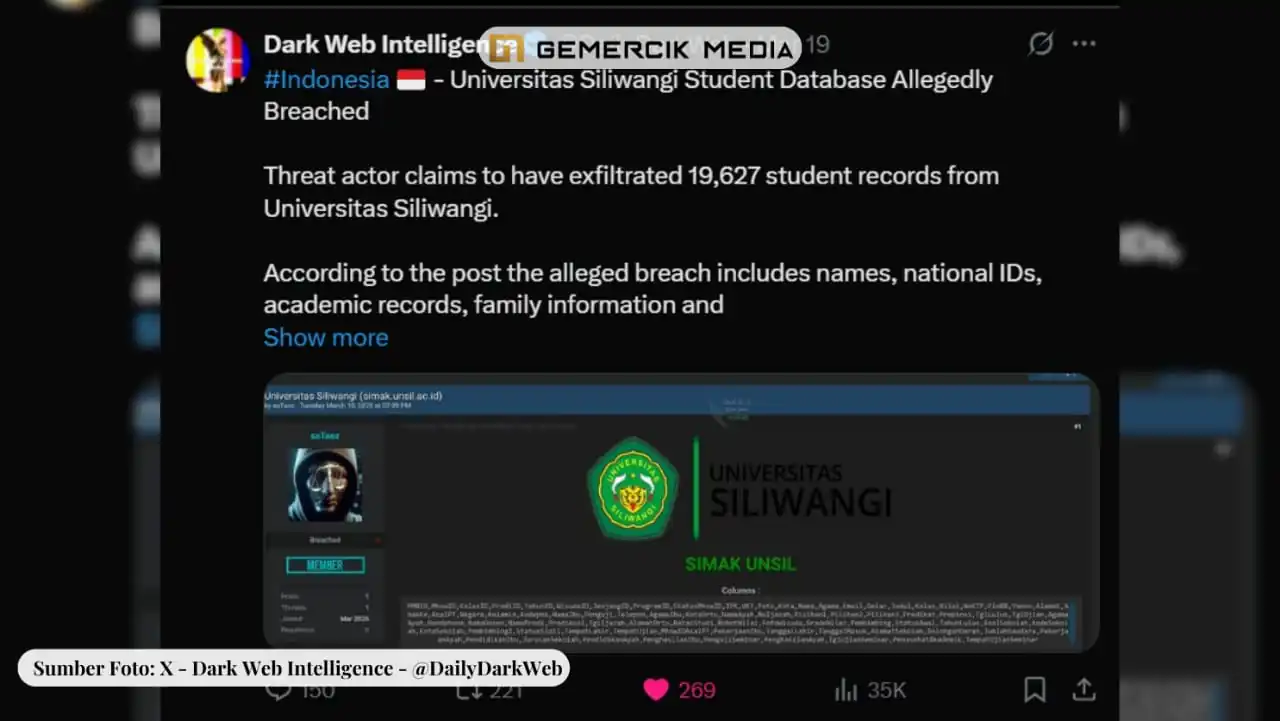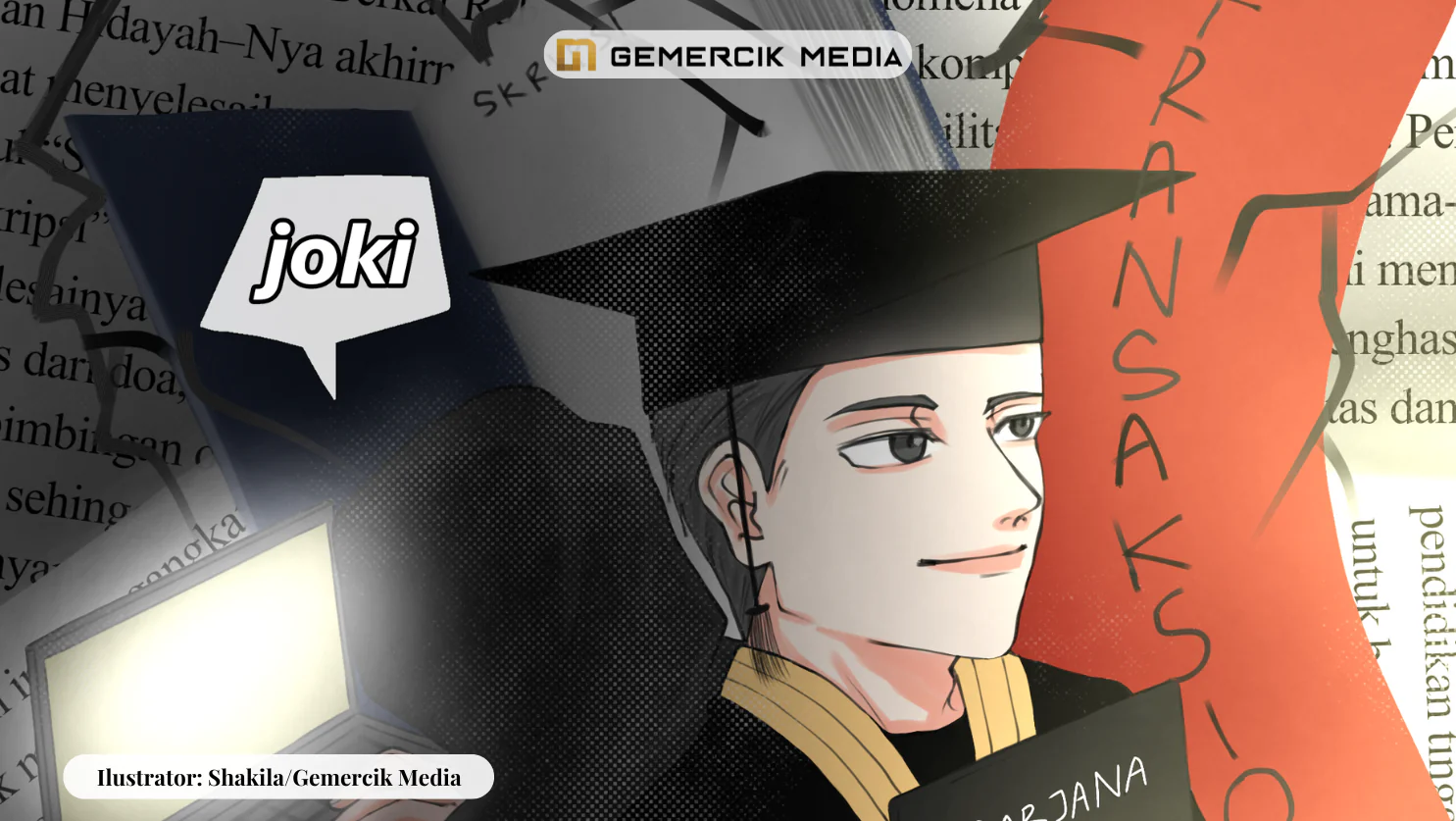Oleh: Ayu Sabrina B.
Di awal tahun 2021, Myanmar menghadapi kondisi genting setelah pemerintahan Presiden Win Myint digulingkan yang berujung pada penahanan Aung San Suu Kyi yang merupakan tokoh demokrasi di Myanmar. Myanmar juga disebut-sebut sebagai ‘Negeri Para Jenderal’, bagaimana tidak keterlibatan dan power militer dalam tubuh pemerintahan begitu besar. Militer berkuasa sebanyak 25% dari total kursi parlemen di bawah konstitusi Myanmar dan juga beberapa posisi menteri yang strategis menjadi pos untuk para penguasa militer.
Satu Februari merupakan mimpi buruk bagi warga Myanmar, setelah Presiden Win Myint dan penasehat pemerintahan sekaligus tokoh demokrasi di Myanmar Aung San Suu Kyi, dijadikan tahanan rumah oleh militer Myanmar. Akses komunikasi tertutup, perekonomian pun lumpuh setelah militer mengkudeta pemerintahan. Militer Myanmar menuding adanya kecurangan pada pelaksanaan pemilu yang digelar pada November 2020 lalu. Ketidakpuasan militer terhadap hasil pemilu dengan menuding terjadinya 10 juta kasus pelanggaran pada pemilu tentunya setelah kudeta terjadi. Jenderal Min Aung Hlaing memegang sementara kendali di pemerintahan dan juga negara Myanmar.
Perlu diketahui, kudeta militer tersebut bukanlah yang pertama di Myanmar, bahkan sempat terjadi pada saat negara ini masih bernama Burma. Dimulai sejak tahun 1962, kala kudeta dilakukan oleh Jenderal Ne Win yang menjadi cikal bakal pertama kalinya pemimpin-pemimpin berlatarbelakang militer berada di Myanmar. Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, mengkudeta pemerintahan semi-demokrasi pada tahun 1962. Tatmadaw menguasai pemerintahan Myanmar hingga berpuluh-puluh tahun dan sepanjang rezim itu muncul berbagai gerakan demokrasi.
Kudeta militer yang terjadi di tahun 2021 tersebut mengundang beragam reaksi, ratusan ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar menolak militer. Sebanyak 38 orang tewas dalam sehari, bagaimana tidak lawan dari masyarakat sipil tersebut adalah mereka ‘Tatmadaw’ yang jelas telah lihai memainkan senjata dan berperilaku refresif terhadap masyarakat sipil. Pertumpahan darah tersebut terjadi satu hari setelah negara-negara tetangga menyerukan pengekangan.
Tetapi menurut penulis, masyarakat sipil di Myanmar sebetulnya hanya bereaksi terhadap kemelut kudeta politik tersebut dan mereka berdemonstrasi karena mereka sudah ikut pemilu yang hasilnya dikhianati oleh militer. Militer Myanmar memang berkali-kali mengubah konstitusi hanya demi mempertahankan kekuasaannya. Ini bukanlah sengketa pemilu biasa, yang kemudian membuat semua orang bisa duduk bersama di satu meja dan menyelesaikannya begitu saja. Apalagi, kudeta militer ini telah menumpahkan banyak darah masyarakat sipil yang membela hak-haknya.
Mengapa kekerasan vis a vis ini bisa terjadi? Pemerotes menilai negara, dalam hal ini aparat, sudah kelewat batas. Benar, negara berhak melakukan kekerasan, bahkan memegang monopoli atas tindak kekerasan. Namun, wewenang itu punya batas. Negara tidak boleh sewenang-wenang. Melanggar batas bukan hanya membuat negara digugat tetapi mendorong negara memasuki fasemengahancurkan diri sendiri. Dari masa ke masa sejarah mencatat banyak negara jatuh akibat kesewang-wenangan yang serupa ini.
Sebenarnya, ada hal konkret yang bisa dilakukan dari kudeta berdarah Myanmar ini. Pertama, militer harus dihilangkan semua pengakuan internasionalnya bahwa mereka mewakili Myanmar, baik untuk diplomat atau pemimpin negaranya saat ini. Negara-negara di dunia apalagi di ASEAN harus tidak mengakui lagi pengakuan internasional terhadap militer Myanmar. Karena, jelas yang dilakukan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap warga negaranya sendiri. Kedua, senjata seharusnya dipantau secara internasional pergerakannya dan dihentikan pasokannya ke Myanmar. Ketiga, di tingkat internasional seharusnya bisa lebih tegas dengan segera memberikan hukuman dan mengatakan penghentian kegiatan militer di Myanmar.
Memang pihak militer Myanmar sebetulnya sudah siap untuk melakukan kudeta sejak 4 tahun lalu, pada saat kasus Rohingnya meletus. Negara-negara di sekitar ASEAN, khususnya yang paling dituakan oleh Myanmar yakni Thailand, merupakan sahabat dekat dari militer Myanmar. Thailand diibaratkan sebagai pintu belakang bagi pemerintah Myanmar, kalau kerjasama dengan Cina itu tidak berjalan dengan optimal. Maka, Myanmar akan meminta tolong pada Thailand. Jadi jika kita perhatikan, tipis sekali kawasan-kawasan perbatasan. Kalau sampai di tingkat internasional terjadi sanksi, tetapi mereka tidak memerhatikan nasib para kaum sipil dan cepat membiarkan militer memegang kuasa, maka mereka (kaum sipil) bisa dibunuh dengan lebih keji oleh Junta militer.
Di samping itu kita perlu memerhatikan dan berhati-hati terhadap narasi yang dimunculkan pihak militer, seperti ‘kondisi darurat’ di Myanmar hari ini yang diberlakukan oleh Junta Militer. Mengutip dari laman CNN Indonesia, bahwa dalam konstitusi 2008 di Myanmar maka pihak Junta Militer mempunyai hak untuk berkuasa ketika situasi seakan-akan sedang mengalami ancaman disintegrasi, akibat kegiatan kekerasan terutama yang sifatnya bersenjata.
Tetapi, kita bisa melihat sendiri bahwa sejak awal kasus pada Februari 2021 dikumandangkan, sebenarnya tidak ada yang memegang senjata selain militer sendiri, sampai hari ini. Jadi, memangnya siapa yang mau melakukan disintegrasi tanpa sejata? Dan yang melakukan pembunuhan pada warga negaranya sendiri adalah militer. Selama bertahun-tahun partai NLD selalu menang dalam pemilu dan konstitusinya diubah terus supaya hal tersebut tidak terjadi. Sehingga, narasi dari militer harus diwaspadai. Karena, memang cara militer Myanmar untuk bisa bertahan adalah dengan memastikan bahwa stabilitas itu bisa terjadi asalkan militer yang berkuasa.
Menilik kekuasaan militer dalam politik Myanmar yang diperkuat konstitusi negara, kudeta bukan hal yang mengejutkan. Demokrasi Myanmar akan terus dirongrong oleh militer yang ingin menguasai pemerintahan. Militer yang menguasai sumber daya ekonomi negara, termasuk kekuatan senjata, dengan mudah menyingkirkan kekuasaan sipil. Oleh karena itu, pengekangan militer untuk terlibat di dalam politik negara menjadi jalan bagi demokrasi untuk bisa berkembang di Myanmar. Namun, bagaimana mengembalikan militer ke barak jika kekuasaannya terlanjur kuat masuk dalam sendi-sendi pemerintahan? Negara lain sepertinya bisa belajar dari Myanmar, bahwa tetap menolak fungsi ganda (dwi-fungsi) militer dapat mempertahankan demokrasi.
Penyunting: Aneu Rizky Yuliana & Rini