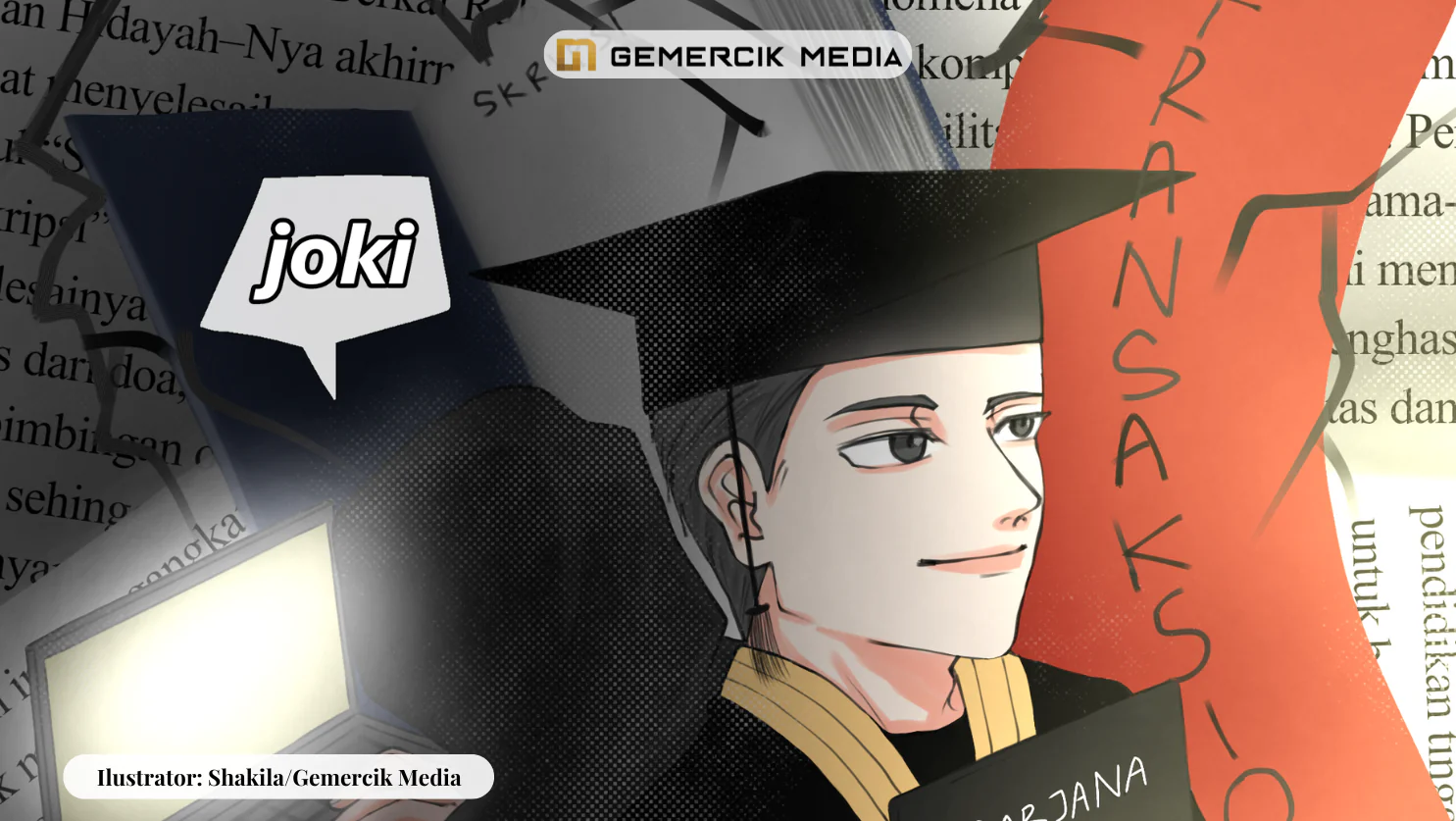Penulis: Khumairoh
Berbicara soal bencana, baru-baru ini, wilayah Indonesia kembali mengalami bencana gempa bumi, tepatnya di daerah Cianjur, Jawa Barat. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 5.6 ini terjadi pertama kali pada tanggal 21 November 2022 lalu. Hingga sampai 25 November 2022, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat ada 248 gempa susulan (aftershocks) yang terjadi di Cianjur.
Mengutip dari Kompas.com, gempa susulan yang terus menerus terjadi di Cianjur ini memakan ratusan korban jiwa, serta ribuan lainnya mengalami luka-luka. Kondisi yang memprihatinkan ini pun menjadi perhatian banyak kalangan. Mereka membuat tagline #PrayForCianjur sebagai bentuk duka cita terhadap bencana yang menimpa warga Cianjur. Segala macam bantuan diberikan, mulai dari pakaian, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Di situasi pasca bencana seperti ini, memang seharusnya bantuan dapat tersalurkan secara cepat dan merata agar dapat memenuhi kebutuhan para korban yang masih selamat.
Namun, sayangnya, masih banyak warga mengeluh, bahwa donasi yang mereka terima belum bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya dalam hal pemenuhan gizi. Kebanyakan makanan yang mereka terima adalah mi instan, yang kita tahu bahwa mengonsumsi mi instan secara berlebih tidak baik bagi kesehatan. Belum lagi, di sana juga terdapat korban balita dan ibu hamil, yang tentunya sangat memerlukan asupan gizi yang cukup.
Keadaan darurat gizi pasca bencana memang sering terjadi, tetapi hal ini tidak bisa terus menerus dimaklumi. Pelayanan gizi pasca bencana ini sebenarnya sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Layanan pangan dan gizi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penanganan kedaruratan. Namun, dalam praktiknya, penanganan gizi pasca bencana belum bisa berjalan dengan baik.
Layanan Gizi Dalam Kedaruratan (GDK) memiliki dua tujuan dasar yang harus terpenuhi. Tujuan pertama, yaitu menyelamatkan kehidupan para korban agar keluar dari krisis melalui bantuan Food for Life. Kedua, membantu kelompok masyarakat yang paling rawan dalam waktu krisis dalam kehidupannya, melalui bantuan Food for Growth (Bhatia, 2002).
Penanganan krisis pangan dan gizi pasca bencana tidak boleh dilakukan semata-mata karena belas kasihan, tetapi juga perlu dirancang dengan cermat dan melibatkan para ahli dari berbagai bidang, seperti ahli gizi, pengelola program penanggulangan bencana dan konflik, serta pengambil kebijakan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan juga adalah jumlah dan kualitas bantuan pangan untuk korban bencana. Makanan yang diberikan ini harus mencukupi kebutuhan korban selama krisis yang mereka alami. Distribusinya pun harus dilakukan secara merata dan terjamin.
Banyaknya kejadian bencana di Indonesia, ternyata tidak membuat pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah (Ormop) semakin tanggap dalam mengatasi krisis pangan akibat bencana. Mereka belum bisa bertindak secara cepat dan tepat dalam menghadapi situasi krisis. Bahkan, kepekaan mereka terhadap krisis pun masih rendah. Dalam situasi bencana seperti yang sedang dialami warga Cianjur ini, masyarakat sangat bergantung pada bantuan dari luar untuk mendapatkan makanan yang layak konsumsi dan bisa memenuhi gizi mereka.
Penyaluran bantuan makanan juga tidak semudah yang kita bayangkan. Bantuan makanan untuk pengungsi dewasa tidak begitu masalah dibanding dengan bayi dan anak-anak. Logikanya, pengungsi dewasa mungkin masih bisa mengonsumsi berbagai jenis makanan, tetapi tidak dengan pengungsi anak dan bayi. Masalah makanan untuk pengungsi anak dan bayi nyatanya lebih rumit, karena mereka belum dapat mengkonsumsi semua jenis makanan yang diperoleh dari tempat penampungan.
Krisis pangan yang menimpa korban bayi dan anak-anak akan meningkatkan risiko terjadinya kurang gizi pada mereka. Dalam kondisi yang lebih buruk, mereka akan menderita marasmus dan kwashiorkor. Anak yang tumbuh dengan penyakit ini akan menjadi generasi yang intelegasinya sangat rendah dan menjadi generasi yang hilang (loss generation). Oleh karena itu, kajian gizi pasca bencana juga perlu terus dikembangkan guna menjaga derajat kesehatan para korban bencana.
Para ahli gizi dan pengambil kebijakan harus mempunyai arah gerak yang selaras. Kesenjangan di antara mereka perlu diminimalkan atau, bila perlu, dihilangkan. Pelatihan GDK juga perlu ditingkatkan terutama dalam hal menggali dan menyosialisasikan program. Mereka harus bisa mencapai tujuan yang sudah disebutkan di atas. Dengan begitu, maka akan terbentuk kebijakan yang sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi, utamanya dalam hal pemenuhan gizi.
Penyunting: Widia MS