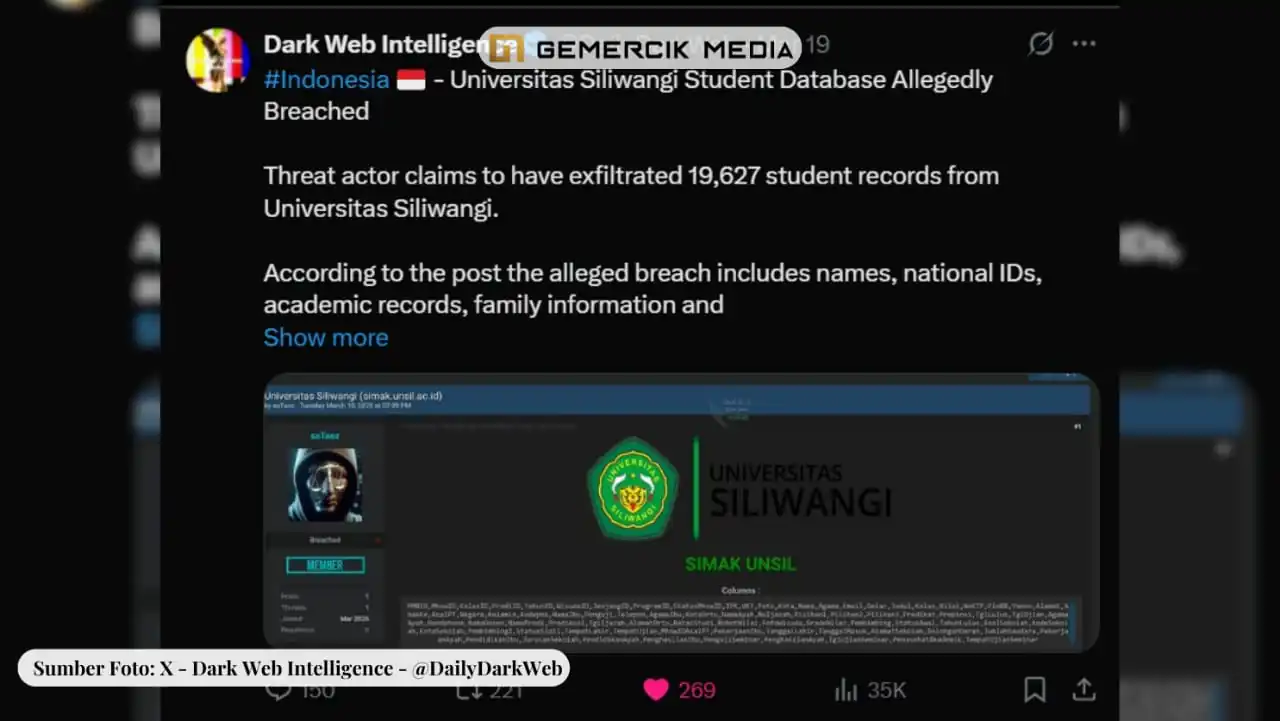Oleh : Asyifa Nurul Rahma Fauziah
Matahari mulai melambaikan tangannya. Gulita perlahan menghampiri. Terlihat sesosok manusia duduk merenung seorang diri. Entah apa yang ia pikirkan saat ini. Tak ada garis senyum yang terlukis di wajahnya. Hanya nampak kerenungan di sana.
Sebelum ini, saat keramaian mengelilinginya, ia menunjukkan senyumnya. Senyum yang ia paksakan lebar-lebar hingga tak ada seorang pun yang mampu memahami tingginya dinding yang ia bangun. Tak ada yang tahu betapa sulitnya ia membuat batas itu. Tak beberapa lama, seorang gadis menghampirinya.
“Kamu beneran gapapa?” tanya gadis itu.
“Haha santai aja. Saya beneran gapapa. Sudah biasa,” jawab seseorang itu.
“Kamu bisa bicara pada ku, jangan sungkan,” timbal gadis itu.
“Haha siap. Kamu sendiri bagaimana? Masalahmu kemarin. Apa baik-baik saja?” ia mencoba mengalihkan pembicaraan.
“Aku baik-baik saja,” jawab gadis itu.
“Syukurlah.” Tambahnya.
Lagi dan lagi, berusaha membangun dinding, berusaha mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Bagai menusuk belati pada jantungnya sendiri. Meretakkan rusuknya secara perlahan. Kretak kretak. Menyisakan sisa-sisa kepingan terakhir. Berharap pada kepingan terakhir ini mampu membuatnya bertahan.
Ditinggalkan oleh orang tersayang, memanglah bukan hal mudah. Ditambah ini bukan pertama kali baginya. Ia takkan pernah siap menerima kenyataan pahit yang bertubi-tubi. Namun dituntut untuk selalu kuat, terlebih di depan adiknya. Kini hanya adiknya yang ia punya.
Mereka duduk di bawah sinar mentari yang perlahan memudar. Seolah tak ada hari esok untuk keduanya. Mencoba meresapi tiap buaian angin yang menyapu lembut wajahnya.
“Mas” ujar adiknya.
“Iya, dek?” jawabnya lembut.
“Bapak, mas” ucap adiknya yang mungil.
Ia terenyuh. Tahu kemana arah pembicaraan ini nantinya. Berusaha untuk tetap terlihat tegar di depan adik manisnya. Tidak mungkin ia mampu menunjukkan keperihan yang ia rasakan juga.
Adiknya masih terlalu kecil untuk menerima semuanya. Masih terlalu mungil untuk berusaha terlihat baik-baik saja. Masih terlalu rapuh untuk menampung beban kehidupan. Saat usia sebayanya bermain ke sana kemari, saat usia sebayanya tertawa riang gembira, saat usia sebayanya tak merasakan apa yang ia rasakan.
“Bapak pasti sudah melihat kita dari atas sana, dek. Bapak pasti tersenyum di langit,” ujarnya pelan sembari menatap awan.
“Kenapa bapak ninggalin kita, mas? Ngga cukup ibu?” air matanya berusaha menyeruak keluar dari kelopak matanya.
“Tuhan lebih sayang mereka, dek. Tuhan pasti telah menemukan ibu dan bapak,” ia mencoba menenangkan adiknya.
“Udah ya nangisnya, bapak ga akan suka liatnya. Nanti bapak sedih. Adik mas kan cantik, nanti ilang loh cantiknya,” tambahnya.
“Tapi, bapak yang bikin sedih, mas” jawabnya polos.
“Dek, bapak ga pernah berniat ninggalin kita. Ibu juga ga pernah pengen ninggalin kita. Tapi Tuhan lebih sayang mereka, dek”
“Udah ya, tuh kan jadi jelek gitu. Kamu masuk ke rumah ya dek, udah mau gelap. Masuk angin nanti,” tambahnya.
“Iya, mas. Adek masuk duluan ya,” ucap adik cantiknya.
“Nah, pinter adeknya mas.” Ujarnya sambil tersenyum.
Kini hanya ia sendirian di sana. Tangisnya pecah tanpa suara. Hanya senja yang menjadi bukti sunyi kepedihannya. Hanya angin yang berusaha menghiburnya. Ia menumpahkan semuanya sendirian. Alam membiarkannya membagi rasa yang ia pendam mati-matian. Hanya saat ini ia tak perlu membangun dinding yang kuat nan kokoh itu.
“Tuhan, mengapa? Tak bisakah? Tak cukupkah? Mengapa waktu begitu singkat?” Ia menghela napas perlahan.
“Adit tahu, Adit hanya anak yang tak berguna. Adit bahkan belum sempat membuktikan apapun. Tapi kenapa? Apa ini sebuah hukuman? Bukannya ini terlalu sulit?”
“Lalu, bagaimana dengan adek? Gimana mungkin cuma Adit dan adek, pak? Gimana cara kami bertahan ke depannya pak? Dia terus menangis, pak. Sebelum ini, saat ditinggal ibu, bapak yang membuat kami kuat. Lalu sekarang bagaimana? Bapak bahkan gaada di sini” ia menumpahkan keluh kesah sesak di dada.
Matahari terus-menerus menenggelamkan dirinya. Bahkan waktu pun tak membiarkannya kali ini. Daun-daun menari seperti mengatakan ‘Ayo kamu kuat!’ padanya. Bulan bahkan mulai terlihat lebih jelas dari sebelumnya.
Ia menghela napas kasarnya berkali-kali. Berusaha membangun benteng kembali dirinya. Bertahan pada sesuatu yang bahkan bisa hancur kapan saja. Setidaknya adiknya penguat satu-satunya saat ini, pikirnya. Bukan, dinding itu bukan untuk dirinya, rupanya. Batas itu ia bangun demi menjaga adiknya.
Kini sepenuhnya mentari telah menghilang, digantikan rembulan ditemani para bintang cantik. Ia menyukai langit malam. Setidaknya dulu, saat ujian itu belum datang bertubi-tubi. Seakan mengeroyoknya ramai.
Pada akhirnya ia harus kembali pada kenyataan. Menguatkan dirinya, memupuk kembali serpihan-serpihan harapan hampir punah. Ia cukup sadar, dunianya runtuh namun dunia yang lain tetap berjalan. Ia menatap langit, tersenyum pedih mengatakan, “Pak-bu, Adit bisa kuat. Jangan khawatirin kami. Tenanglah di sana. Insyaallah, kami ikhlas. Adit sayang kalian”. Ia menyeka air matanya. Menarik napas dalam-dalam. Meyakinkan dirinya untuk bertemu adiknya kembali. Perlahan tapi pasti, langkah kaki itu akan kuat, dan akan semakin menguat.
Penyunting: Rini