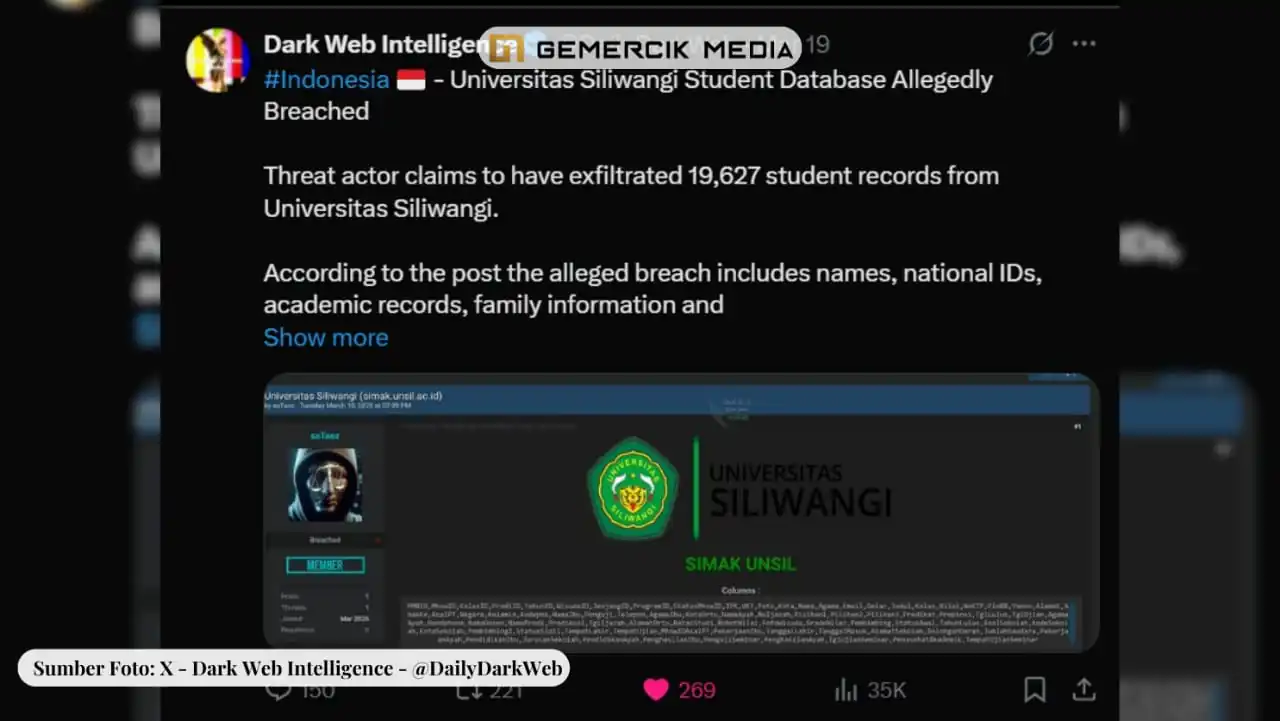Oleh: Wiku Rajidae
Dunia sudah asing, arloji miliknya berputar hanya untuk melihat ia menggantungkan nasib di kursi kayu tua. Dinding yang memajang lukisan hasil anak bungsunya dan langit-langit rumah setengah abad miliknya. Kadang kala, terdengar gerit engsel pintu terbuka atau tertutup ketika cucunya hendak pergi dan pulang menuju rumah. Kadangkala, geritannya diselingi hela napas berat milik anak sulungnya. Namun, yang jelas ia tahu, suara orang bersahutan menghitung jumlah kematian dari televisi lah yang menjadi penghuni tetap ruangan ini.
Matahari sedang dicuci di pekarangan rumah. Pagi itu, ditepisnya langit biru menjadi kelabu yang menghambur tiap tetes mengalir sebuah ingatan dan kerinduan. Ia hanya lelaki tua yang rindu bagaimana dulu sekali, bumi tak terhingga besarnya, sekarang bumi sangat kecil, ia hanya melihat dunia seluas jendela ruang tamu.
“Mau kemana, Nduk?”
“Keluar, Mbah. Kerja,”
“Apa kamu gak kapok liat Mbah Uti dan ibumu meninggal gara-gara Corona?”
“Sudah, Mbah. Jangan dibahas. Aku jelas ingat! Tapi ada nyawa yang harus aku bantu.”
“Kamu saja tak kasihan dengan nyawamu.”
Ia berpaling, sedikit-sedikit melirik cucunya yang sedang memakai masker dan beranjak dari beranda. Bukan maksud hati melarang cucunya mencari pundi-pundi uang dan memenuhi tanggung jawab, bukan maksud hati mengungkit perih dari luka yang belum pulih. Ia hanya sedang mengaku kalau dirinya adalah seorang penakut yang tak ingin satu-persatu ditinggalkan orang-orang terkasih. Ia sudah sakit hati kesekian kalinya.
Masih ia ingat bagaimana hangat dan harumnya teh menguar sebagai alarm untuk bangun lebih pagi, duduk dengan sang istri sebagai teman berbagi pikiran yang berjanji sehidup semati. Sudah 113 hari, manis teh terasa pahit di lidahnya bersamaan lenyap membawa anak dan istri tercinta menuju liang lahat, bahkan sebelum ia mengucap salam, ia tak sempat melihat senyum mereka terakhir kalinya.
Kalau saja, kalau saja dunia sedang tidak jahat, jejak-jejak kaki di rumah ini akan ramai dan hangat karena anak-anak dan cucunya berkumpul. Tiada suara detik jam bergaung menyesakkan seakan mendikte kematian, tiada suara kesah menunggu dering “gawai” dari sanak di perantauan sana bertanya perihal basa-basi yang membahagiakan.
Ini terlalu sunyi.
Ini bukan sunyi yang bisa diobati.
Ini bukan sunyi yang bisa diisi.
Ini bukan sunyi yang bisa diganti.
Ini sunyi yang abadi.
Editor: Rafi Setyadi