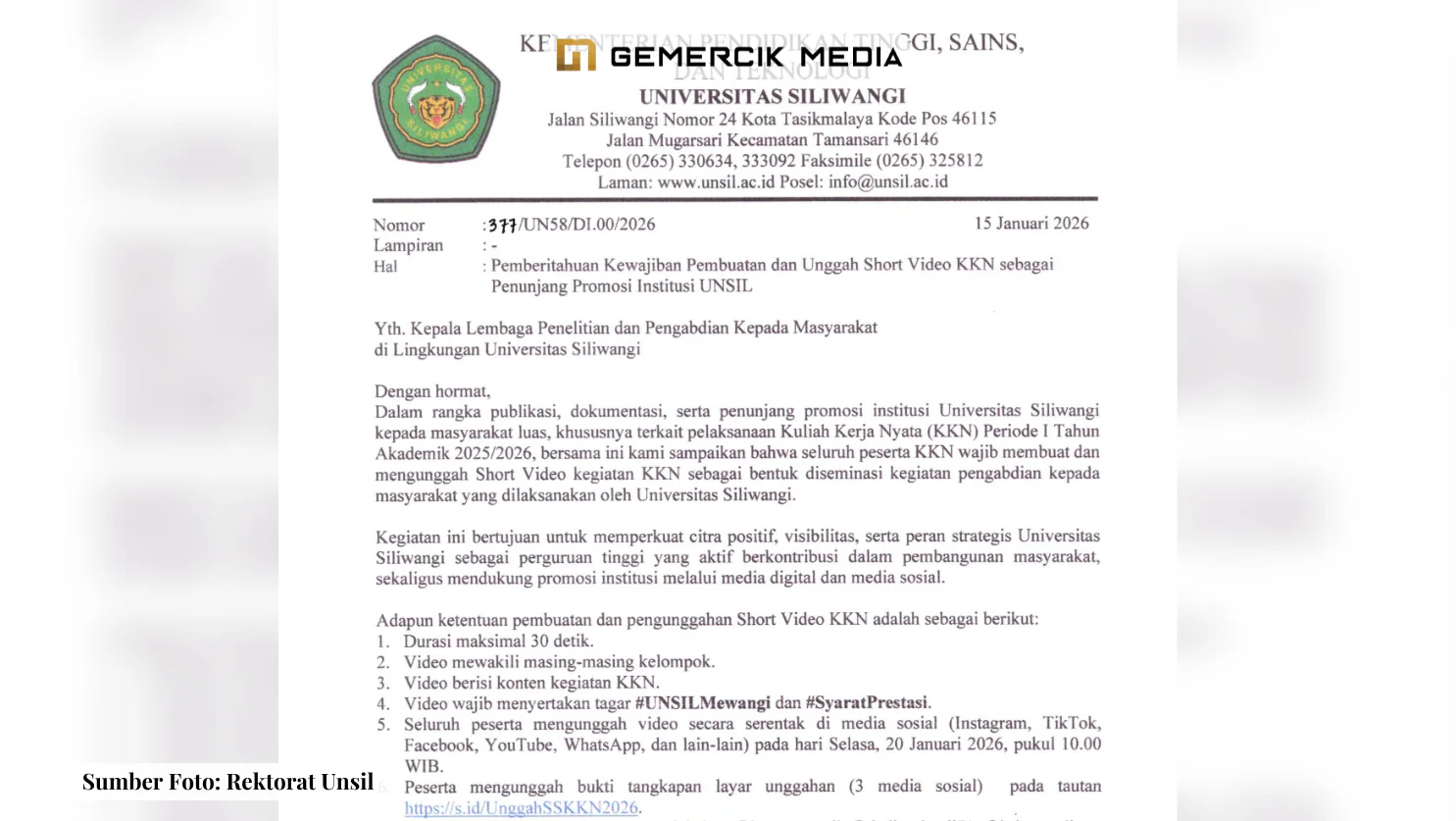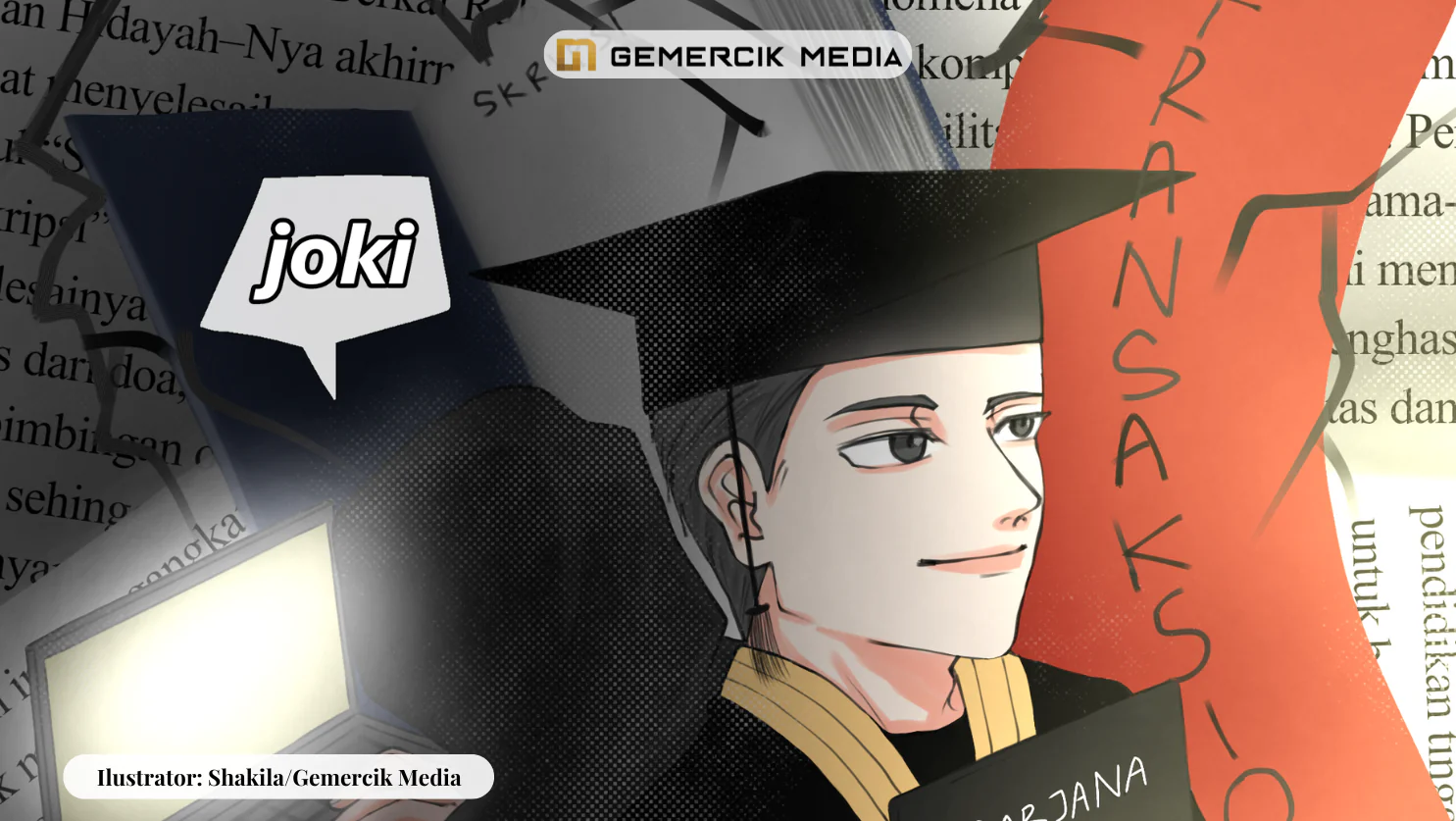Oleh, Erika Nofia Pransisca Permatasari
Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perlu dihadapi dengan serius. Melalui kebijakan di tingkat kampus, masalah serius seperti ini juga harus dipayungi oleh kebijakan negara. Tingginya kasus prevalensi kekerasan terhadap perempuan, ibarat fenomena gunung es yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya atau terbatasnya wadah pelaporan dan pencatatan kasus, bahkan tidak semua kasus berani dilaporkan.
Tahun 2019 lalu, tirto.id bersama VICE Indonesia, dan The Jakarta Post melakukan kolaborasi #NamaBaikKampus. Salah satu bentuk upaya dokumentasi dari penyintas kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil laporan tersebut mengatakan, dari 207 koresponden, terdapat 174 kasus kekerasan seksual yang tersebar di 79 perguruan tinggi di 29 kota di Indonesia. Di mana mayoritas penyintas merupakan perempuan dan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi di Pulau Jawa.
Komnas Perempuan mencatat sedikitnya ada 15 jenis kekerasan seksual yang dialami perempuan Indonesia. Setiap 2 jam, ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Namun, hanya 10% yang berani melapor ke Kepolisian, 5% yang diproses oleh hukum, dan hanya 3% yang divonis. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih ditemani dengan ketimpangan gender yang tinggi. Budaya patriarki yang masih mendarah daging patut menjadi perhatian. Sebab, catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat 431.471 kekerasan terhadap perempuan dengan 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah pribadi dan 3.602 kasus kekerasan seksual di ranah komunitas/publik.
Sulitnya mendapatkan informasi khusus tentang kejahatan seksual di ranah perguruan tinggi menjadi hambatan setiap penelusuran. Tirto.id dalam artikelnya juga menuliskan minimnya data yang komprehensif mengenai kasus ini membuat mereka kesulitan mengidentifikasi seberapa sering prevalensi kasus kejahatan seksual di kampus, siapa pelakunya, dan siapa korbannya. Padahal, data seperti ini sangat dibutuhkan demi menguatkan ungkapan bahwa kasus seperti ini sudah “jadi rahasia umum kampus”.
“Di negara kita, kekerasan seksual sering dikaitkan dengan moralitas, apalagi kalau terjadi pada perempuan dewasa. Kalau pada anak-anak, jelas semua orang pasti mengutuk pelaku. Tapi, kalau perempuan dewasa biasanya sangat erat dengan konteks moral dan agama,” ujar Sophia Hage, salah satu pendiri Yayasan Lentera Sintas Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. (Dikutip dari tirto.id)
Buruknya stigma yang melekat pada para penyintas kejahatan seksual seringkali membuat mereka akhirnya memilih bungkam. Selain itu, budaya perkosaan yang merupakan anak dari budaya patriarki memunculkan pandangan yang menganggap bahwa pemerkosaan adalah gejala umum. Nilai-nilai misoginis dan seksis yang terbentuk dalam patriarki menempatkan perempuan dan feminisme berada di bawah kepentingan maskulinitas. Seperti yang ditulis tirto.id dalam artikelnya, kekerasan seksual, ujar Sophia Hage, kerap terjadi karena ada ketimpangan kuasa. Di kampus, peristiwa ini biasa terjadi antara dosen dan mahasiswa. Dengan mudah dosen akan mengintimidasi mahasiswa lewat otoritasnya. Semisal menahan skripsi, menolak jadi pembimbing studi akhir dan sebagainya. Apalagi jika dosen tersebut punya prestasi dan ternama di kampus.
Selain relasi kuasa yang digunakan oleh oknum demi memuaskan hasratnya. “Victim-Blaming” menjadi salah satu alasan tertinggi di lingkungan mana pun serta membuat para penyintas memilih diam. Komentar-komentar negatif merupakan hal yang paling sering diterima ketika seorang penyintas menceritakan apa yang dialaminya seperti “Makanya jadi cewek jangan keganjenan” atau “Makanya pake baju yang sopan, yang tertutup gitu” menjadi bukti maraknya budaya menyalahkan korban.
Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
Testimoni penyintas kekerasan seksual yang berhasil dikumpulkan oleh kolaborasi #NamaBaikKampus dalam rentang 13 Februari–28 Maret 2019 menerima 174 pengaduan. Sebanyak 129 penyintas menyatakan pernah dilecehkan, 30 penyintas mengalami intimidasi bernuansa seksual, dan 13 penyintas menjadi korban pemerkosaan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami para penyintas adalah sebagaimana yang terdapat dalam RUU PKS, yakni pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
Pelaku kejahatan seksual di perguruan tinggi sangat beragam. Sebagian besar diantaranya adalah civitas academica di perguruan tinggi tersebut. Seperti dosen, mahasiswa, staff, ahli agama, dokter di klinik kampus, hingga warga di lokasi KKN. Kejadiannya pun tidak hanya terjadi di lingkungan kampus, melainkan di luar kampus seperti kos-kosan, rumah dosen, tempat magang, lokasi KKN, klinik kampus, hingga kejahatan berbasis teknologi.
Kasus kejahatan seksual di Perguruan Tinggi marak terjadi justru pada kampus ternama. Kasus kejahatan seksual mulai mencuat ke permukaan dan ramai diperbincangkan ketika balairung press menerbitkan laporan investigasi terhadap Agni, salah satu penyintas kekerasan seksual di UGM. Disusul para penyintas dari si pelaku Ibrahim Malik di UII. Kekerasan Seksual di UI, UNJ, UNP, USU bahkan PTKI. Kejahatan seksual akhirnya menjadi penting dibicarakan. Menuntut kemendikbud dan pihak kampus membuat kebijakan tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta ramah perempuan.
Kasus Agni telah memberi fakta bagaimana UGM mengabaikan kasus kekerasan seksual di kampus. Dilansir dari tirto.id, Agni menuntut UGM mempunyai mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih jelas definisi, tahapan penanganan dan sanksi terhadap pelaku, serta penanganan dan pemulihan hak-hak penyintas agar kasus kekerasan seksual di lingkungan akademik tak terulang lagi. Pada 18 Januari, kolaborasi #NamaBaikKampus sempat bertanya kepada Agni atas kasusnya. Agni berkata ia berharap UGM tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. “Tapi, selama setahun setengah, terlihat tidak tegas terhadap pelaku. Bahkan UGM seperti tidak mau mengakui bahwa ada ‘pelecehan seksual’.”
Berbeda dengan kasus Agni di UGM, Dias, Alumnus Universitas Diponegoro juga menceritakan insiden yang menimpanya ketika masih berstatus mahasiswi. Jika pelaku pada kasus Agni adalah seorang mahasiswa, Dias menceritakan pengalamannya menjadi penyintas kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dosen di jurusannya. Setelah melaporkan kasusnya kepada pihak dekanat, kasusnya justru dianggap bukan pelanggaran yang berat dan berakhir menggantung. Bahkan kejadian tersebut tak hanya berhenti di Dias. Gia, Iriana, dan Vani adalah penyintas lain dari pelaku yang sama.
Tidak hanya dua kasus di atas, masih banyak kasus-kasus lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Dua kasus di atas seharusnya memberi tamparan kepada pihak kampus agar serius dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Serta memberikan peringatan kepada kampus lain tentang pentingnya sebuah kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tidak cukup sampai di sana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menaungi perguruan tinggi juga harus membuat paying hukum yang kuat untuk meminimalisasi kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan pendidikan. Karena kekerasan seksual tidak hanya terjadi di perguruan tinggi, melainkan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut menjadi penting dengan tujuan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman serta ramah perempuan.
(Tulisan ini dikutip dari berbagai sumber)
Penyunting: Rini