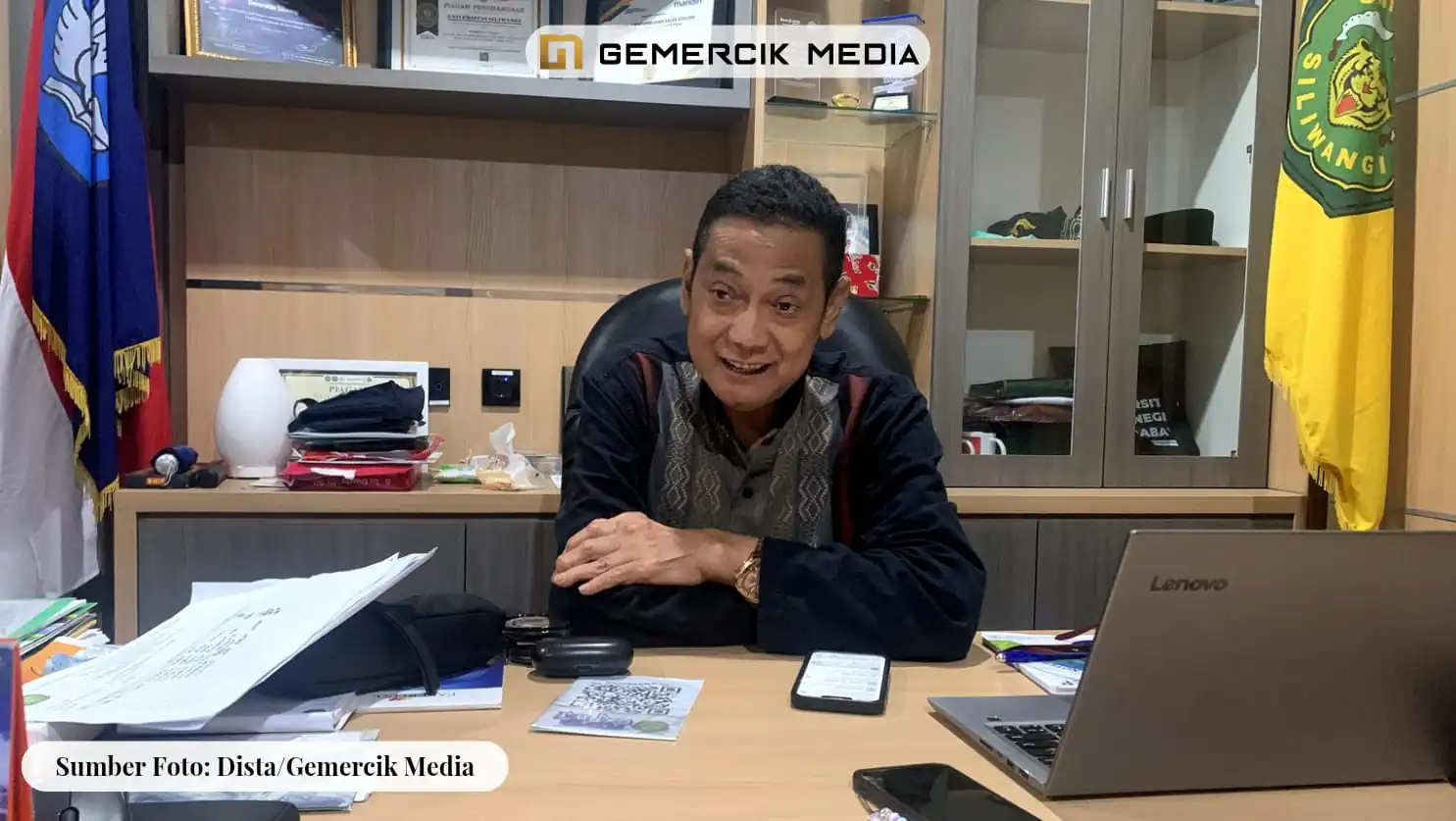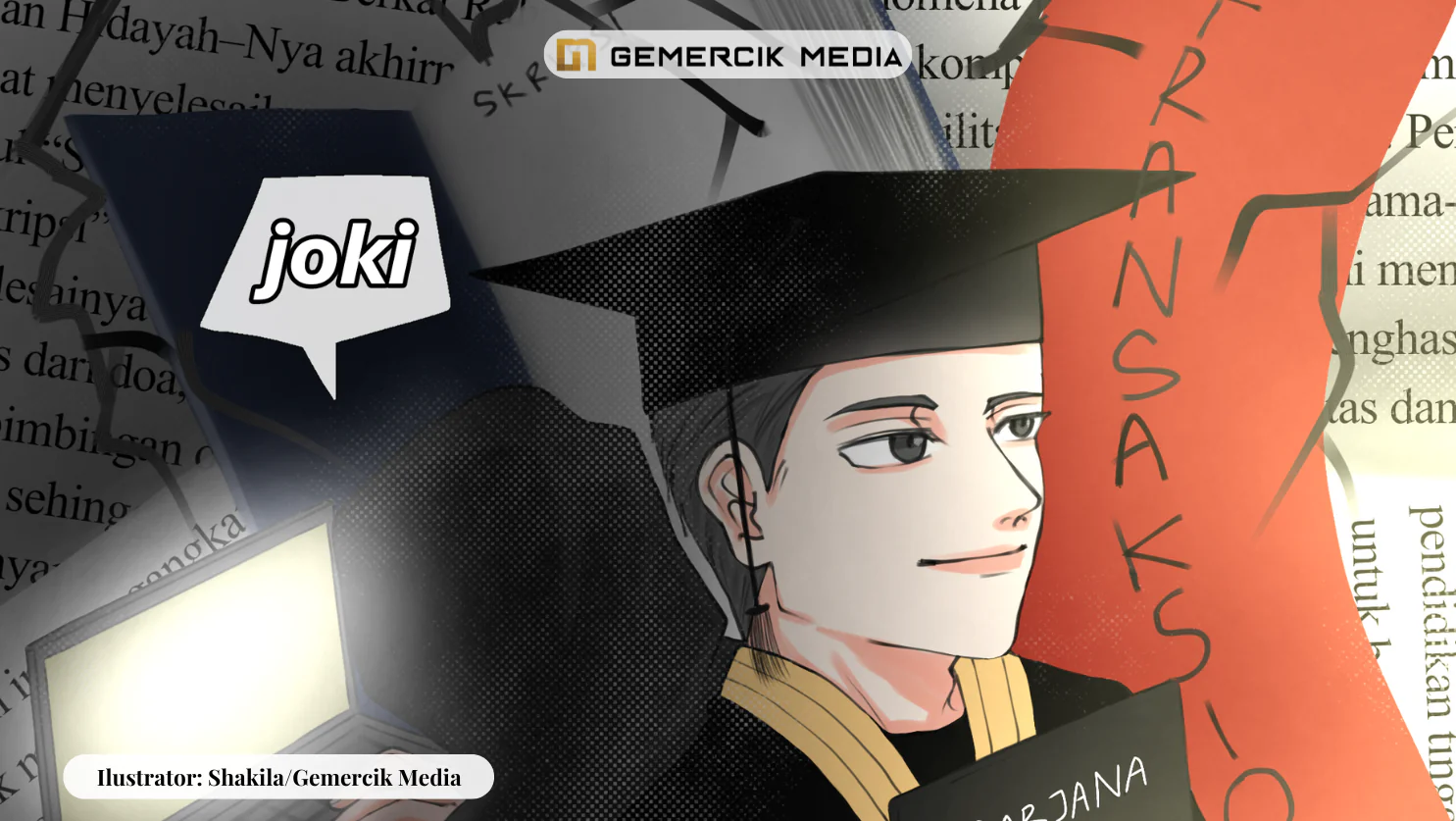Oleh : Bagus Rhizky Wiyanto Saputro
Seseorang yang telah memantapkan dirinya untuk tidak jauh dari dunia informasi sebagai jurnalis layak disebut pejuang hak asasi manusia (HAM). Mengapa demikian? Sebab manusia pada dasarnya berhak memperoleh informasi, terutama saat ini informasi tidak lepas sebagai suatu kebutuhan. Pemenuhan informasi kepada masyarakat inilah salah satu perwujudan dari hubungan jurnalistik dan hak asasi manusia. Di Indonesia, UUD 1945 dan produk-produk hukum turunannya menyebutkan adanya hak kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berserikat bagi masyarakat. Selain itu juga diakui hak kebebasan mencari, menerima, dan mengungkapkan informasi.
Bahkan pada tahun ini, jurnalis tetap memperjuangkan HAM dengan keadaan yang diselimuti pandemi COVID-19. Jurnalis tanpa henti membela hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak kesehatan dan hak-hak lainnya, yang intinya adalah hak keselamatan dari peliknya keadaan yang sedang dialami masyarakat. Wujud tindakan yang nyata misalnya menginformasikan fakta kesulitan ekonomi.
Dari pekerja harian yang kehilangan pencaharian. Contoh lainnya adalah kritikan jurnalis secara terus-menerus terhadap ketidaksempurnaan dari kebijakan pembelajaran secara daring yang diterapkan oleh pemerintah, dengan alasannya menyulitkan kehidupan masyarakat kelas ekonomi bawah. Keadaan masyarakat dalam kedua contoh di atas juga situasi yang akhirnya berhasil diperjuangkan kandungan hak asasi manusianya oleh jurnalis. Hasilnya pemerintah mengencarkan bantuan sosial kepada masyarakat dan terbaru adalah memberikan kuota internet gratis bagi pelaku dalam dunia pendidikan.
Dalam perspektif sebagai mata dan telinga masyarakat, jurnalis mempunyai suatu privilege pada kognisi dan afeksi penerima informasinya. Keistimewaan tersebut dalam wujud kemudahan bagi jurnalis untuk memengaruhi orang lain. Hampir semua orang menganggap karya jurnalistik sama halnya dengan kebenaran sehingga mudah sekali dijadikan referensi masyarakat. Namun demikian, maraknya peredaran berita yang tidak benar saat ini, termasuk yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan bagi kehidupan jurnalistik. Hal semacam itu membuat masyarakat menjadi risau, yang tidak menutup kemungkinan pada akhirnya menganggap semua jurnalis tidak lebih dari sekadar penyebar kebohongan. Dampak ini juga mampu membuat hak asasi manusia yang ingin dibawa oleh jurnalis menjadi terkesan kabur dan dianggap omong kosong. Padahal jurnalis yang seutuhnya tidak akan dengan mudah mendistribusikan informasi. Bukti-bukti empiris terlebih dahulu dikumpulkan, diolah, dan yang paling penting dipastikan secara benar tingkat akurasi dan relevansinya sebelum dijadikan warta dan informasi.
Ada sekat-sekat yang harus menjadi pisah batas antara tindakan yang tepat dan tindakan jurnalis yang keliru. Tepat bagi jurnalis untuk mengabarkan suatu hal yang relevan dengan kepentingan stakeholder terkait dan keliru, jika memilih menyebarkan informasi yang tidak mempunyai keterkaitan dengan pemangku kepentingannya. Sebagai contoh, risih rasanya melihat jurnalis terlalu masuk ke dalam urusan pribadi seorang individu dunia selebritis. Hal ini karena setiap orang memiliki tanda-tanda kehidupan mempunyai hak asasi, salah satunya hak privasi. Bahkan terpidana hukuman mati masih mempunyai hak asasi. Bagaimana pun merupakan tindakan yang benar jika mengulik kehidupan seseorang terkait tanggungjawabnya. Ambil contoh lain dengan subjek seorang pejabat publik, segala keputusan dan tindakannya dalam birokrasi wajib diwartakan oleh jurnalis. Namun, karena pejabat publik adalah suatu titipan dan representasi dari rakyat sebagai pemberi amanat, maka penyimpangan individunya dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi sah untuk diwartakan.
Menanggapi tuntutan dari perannya, menjadi sesuatu yang mendesak bagi pelaku jurnalistik untuk segera memilih jalan yang tepat. Suatu koridor menjaga independensi dan merawat nilai kebenaran, serta tetap mengedepankan hak asasi manusia dalam memperjuangkan hak tersebut. Cukup sulit untuk menentukan jalan tengah yang seimbang antara benar dan salah dalam kehidupan jurnalistik. Oleh karena itu, dibutuhkan penalaran moral (moral reasoning). Suatu penilaian yang mendalam dan matang untuk menentukan pilihan ketika terjadi dilema. Harapannya, muncul keseimbangan dalam bertindak dari jurnalis ketika mengawal hak asasi manusia. Jangan sampai jurnalis malah masuk ke dalam permasalahan ranah hukum dan membuat blunder ketika berusaha memperjuangkan fakta. Jangan sampai jalan tengah dengan cita-cita yang mulia menjadi suatu jalan pedang terhadap kemuliaan harfiah jurnalistik.
Menyadari pentingnya pemahaman terhadap hak asasi manusia, tidak dapat dilepaskan dari risiko jurnalis sebagai seorang pelaku aktif perjuangan HAM sepanjang waktu. Terlebih dengan masih seringnya kita menjumpai hak asasi dari jurnalis sebagai pembela HAM juga ikut dilanggar. Bahkan tidak jarang kita menjumpai situasi dan keadaan jurnalis mengalami kekerasan fisik selain ancaman-ancaman lain. Menurut penelitian Osmann dkk. (2020) seperti manusia pada umumnya, jurnalis juga rentan terhadap depresi dan permasalahan psikis lainnya karena pekerjaannya penuh bahaya. Ironisnya hanya segelintir jurnalis yang memperoleh perawatan kesehatan psikis. Berdasarkan penelitian Osmann dkk. (2020) diungkapkan fakta bahwa tempat jurnalis bekerja juga seolah-olah tidak peduli terhadap kondisi yang dialami oleh jurnalis.
Solidaritas dari masyarakat sebagai insan yang telah memperoleh manfaat dan diperjuangkan hak asasinya oleh jurnalis menjadi penting jika melihat risiko dan pengorbanan dalam penyampaian informasi yang syarat nilai. Selain itu, peran aktif penerima informasi dari jurnalis menjadi suatu hal yang mendesak dalam keadaan pandemi, dengan adanya permasalahan distribusi data dan informasi yang keliru. Distribusi kebohongan ini mempunyai motif tersendiri yang jahat. Salah satu penghargaan terhadap seorang jurnalis tergantung dari bagaimana kita sebagai penerima informasi ikut aktif mengoreksi, dan juga melakukan penalaran maupun pengujian kembali terhadap kebenaran suatu berita. Maksudnya adalah kita harus membedakan sosok jurnalis asli dengan nilai-nilai fakta yang dijunjungnya atau jurnalis palsu yang menyamar untuk merusak kemuliaan jurnalis. Kesimpulannya melindungi jurnalis dan martabatnya sama halnya dengan melindungi hak kita semua, hak asasi manusia.
Penyunting: Rini Trisa